Sabtu yang tertunda
Sabtu itu, aku beranikan diri. Aku ajak kamu ngopi. Sebetulnya, bukan hari Sabtu, sih. Tapi lebih tepatnya hari Jumat. Di bawah kolong meja kerjaku. Saat teman-teman sekantor sedang tidak berada di kantor. Aku curi-curi waktu menulis pesan singkat untukmu.
"Hai, apa kamu sibuk akhir pekan ini? Ada manuskrip yang mau aku tunjukkan kepadamu." tulisku, mencari-cari alasan.
Sebetulnya, aku sudah cukup beruntung bisa mengenalmu sebagai teman. Teman yang cerdas, punya minat yang sama dan sering memberiku pekerjaan lepas.
Teman yang enak diajak ngobrol dan lumayan pengertian karena kamu mengantarku pulang sekali-dua kali kita keluar malam. Apa mungkin bisa jadi aku masih terbawa emosi akan sore-sore tenang di kedai kopi, di mana cuma kita berdua ngobrol ngalur-ngidul tentang pekerjaan, keluarga dan terakhir-terakhir ini tentang cinta.
Cinta bukan terkait perasaan tapi cinta pada konteks umumnya. Cinta yang menyebalkan, cinta yang membuat kita menerka-nerka.
Mungkin aku bermimpi, bisa bersanding dengan dirimu sebagai kekasih. Haha. Membayangkannya saja aku geli. Seorang flower boy dengan seorang DUFF--the designated ugly fat friend. Kalau dari luar, kita terlihat terlahir dari dua dunia yang berbeda. Namun, sebetulnya kita juga punya kesamaan, selain sama-sama suka menyendiri.
Kita juga sama-sama masih belum bisa melupakan orang yang dulu kita sayangi. Ups, maaf, sepertinya belakangan ini aku malah sering mengintip akun sosial media kamu. Walau sebenarnya cukup aneh, bukan? Untuk apa aku harus mengintip pikiranmu dari jendela akun sosial, seharusnya aku bisa mengirimkanmu pesan singkat dan menanyakan apa kabar? Karena aku tahu, akan sampai di situ saja percakapan kita.
Hanya berhenti di conteng biru whatsapp. Aku masih ingin berbicara panjang lebar denganmu tapi entahlah tentang apa.
Makanya aku mengajakmu ke sini.
Aku mengambil sudut favoritku di kedai kopi tempat kita bertemu, yang juga adalah kedai kopi favoritku. Aku bersembunyi di balik layar laptopku saat kamu tiba. Kemeja kotak-kotak merah yang sama lagi, tapi rambutmu sudah panjang dari terakhir bertemu. Wajahmu tampak segar, mungkin karena tidak ada tugas pekerjaan.
"Hai," sapamu.
"Hai," nada suaraku melonjak ceria, seolah menyapa teman. "Apa kabar? Bagaimana pekerjaan?"
Kamu tersenyum dan menjawab, "Ya, gitu-gitu aja. Kamu apa kabar? Bagaimana pekerjaan?"
Aku mengangkat bahu. "Ya, kadang sibuk. Kadang nggak. Sekali sibuk..." Aku menggulung bola mataku. Tapi, seandainya kamu tahu aku tidak mengajakmu ke sini untuk bicara tentang pekerjaan atau manuskrip puisiku ini. Aku cuma mau bertemu dengan kamu.
Dan, aku menyahuti, mengiyakan dan menjawab komentarmu terhadap manuskrip puisiku yang kamu puji ini. Entah kamu berprilaku sopan, bagiku manuskripku kurang matang. Tapi, aku melihat lagi garis-garis rahangmu yang keras dan keseriusan di wajahmu yang membuatmu semakin menarik di mataku.
Dengan wajah setampan itu, mungkin mudah bagimu untuk mendapat penggemar. Baik laki-laki atau perempuan. Berbeda denganku. Rasanya aku tidak pernah punya penggemar yang gila. Terkadang aku juga iri, adakah orang di luar sana yang menanggapi aku dengan serius. Rasanya belum ada.
"Kamu baca artikel yang aku kirim?" tanyaku memecah keheningan, mengarahkan pembicaraan editorial menjadi perbicangan yang lain lagi.
"Yang mana?"
"We are the generation who doesn't want a relationship? Dari Huffington Post?"
Air mukamu berubah. "Oh, ya... aku ingat." terus kemudian bibirmu mengatup lagi. Setelahnya, apa?
"Bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju bahwa generasi kita ingin pacaran tapi tidak ingin punya komitmen menjalani hubungan yang ribet?" pancingku.
Dengan sederhana kamu menjawab. "Ya. Aku rasa banyak anak muda punya bayangan tentang cinta, ingin dicintai tapi tidak mau mencintai." kemudian disambut dengan tawa kecilmu, menggemaskan, tapi sekarang agak mengangguku.
"Apa kamu pernah berada di tempat yang abu-abu?"
"Abu-abu?"
"Ya? Hubungan tanpa status? Friends with benefit, whatever the benefit is..."
Tawamu makin renyah. "Ya, beberapa kali. Itu mungkin karena aku belum menemukan yang cocok. Bagaimana denganmu?"
Dengan tenang, aku mengamati gerak-gerikmu. Diam. Membaca satu-persatu kalimat yang aku tulis, yang aku rasa sembarangan ku tulis tapi kamu mangut-manguti seperti setuju. Sekarang dari balik majalah aku menyembunyikan wajahku.
"Kamu tahu dua kali aku melakukan kesalahan dalam hidupku?" lontarku begitu saja. Dengan tenang, membolak-balikkan halaman majalah yang beritanya tidak mengasyikkan bagiku.
Ada pepatah Buddha (yang ternyata palsu), yang berbunyi, "...if you meet somebody and your heart pounds, your hands shake, your knees go weak, that’s not the one. When you meet your ‘soul mate’ you’ll feel calm. No anxiety, no agitation."
Rasanya seperti itu bertemu denganmu. Semuanya seperti terukur, kapan kamu mengatakan iya dan kapan tidak. Benar aku merasakan gugup ketika berada di sekitarmu, namun, aku masih memegang kendali semestaku... atau mungkin saja aku membuat-buat alasan.
Kamu mendongakkan wajah. Mendengarkan sepenuhnya. Wajah yang sama yang kamu tunjukkan saat terakhir kali aku bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah aku sayangi, kemudian menghilang tanpa jejak. Menghapus segala kontakku. Meninggalkan perasaan kecewa dan lebih parah lagi, malu dan hina.
Aku menoleh kepadamu yang sepenuhnya mendengarkan. "Dua kali menyatakan perasaan. Yang pertama terlalu cepat, yang kedua kali terlambat. Aku tahu, tidak biasa perempuan mengatakan perasaan. Tapi, aku bukan perempuan biasa rasanya. Dan benar, mereka hanya menganggapku teman baik, walaupun aku merasakan sesuatu yang begitu kuat dan menunjukkannya dengan sungguh-sungguh." Ku tarik nafasku dalam-dalam, "Maaf kalau ini membuatmu tidak nyaman. Tapi ada yang perlu aku sampaikan."
Air wajahnya tidak berubah. Aku sama sekali tidak bisa menebaknya. Tapi kalut perasaanku dari dulu sudah menjadi perang yang aku geluti selama setahun lebih. Dan mundur, sudah bukan pilihan. Kini, mungkin saja dia tahu dari gelagatku yang lumayan aneh.
"Aku suka menemuimu. Aku suka berbicara denganmu. Aku benar-benar suka dengan kamu." Seperti tarikan nafas ijab qabul, dalam satu tarikan nafas aku mengatakan itu. Bola yang ada di tenggorokkanku yang dulu mencekat nafasku, rasanya menghilang. Ada rasa lega di dada. Dan, aku bisa melihat wajahmu yang memerah, namun tanpa senyum. Yang ada wajahmu makin mengerut.
"Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf kalau aku membuatmu tidak enak. Kamu bisa cerita denganku apa yang kamu rasakan terhadapku. Aku tidak akan merasa kecil hati kalau kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku sudah dewasa dan sudah beberapa kali dikecewakan banyak orang. Kalau kamu tidak memiliki perasaan sama, yang aku syukuri adalah kamu memberi tahu di mana aku berdiri. Dan dari situ aku akan berhenti mengharap. Bukan di tempat abu-abu itu. Aku harap kita bisa menjadi teman, kita masih bisa menulis bareng..."
Nyaliku mulai ciut, karena kini dia mengusap-usap tangannya ke sekujur mulut seperti ada sesuatu yang tidak berani kamu katakan. Sebetulnya, katakan saja! Gerak-gerikmu mengangguku. Karena, aku mengartikan semuanya.
"... Tapi kalau kamu merasakan sebaliknya." tuturku pelan. "Kalau kamu merasakan apa yang aku rasakan, aku akan bahagia. Jujur saja, aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Bayangkan kota besar yang kita tinggali ini, kadang kita bisa dibuat putus asa dan kecewa. Yang kita butuhkan adalah teman setia. Dan kalau itu yang kamu cari, aku ada di sini. Aku akan menghargai kebebasanmu. Sebisa mungkin aku tidak akan menuntutmu untuk meladeniku setiap jam atau setiap detik. Ya, aku juga punya kegiatan. Kamu punya kegiatan. Kita punya dua dunia. Sebisa mungkin aku akan mendukungmu melakukan apa yang kamu sukai. Aku tidak meminta banyak, benar." Aku menutup pidatoku dengan senyum, sambil memainkan jariku di bibir cangkir entah kenapa.
Aku tidak melihat balasan yang berarti dari wajahmu atau dari suaramu. Lantas aku tundukkan wajahmu ke gelas kopiku yang mendingin. "Aku tahu, aku bukan sosok yang kamu bayangkan, bukan sosok yang kamu cari..."
Ya, alangkah bodohnya aku.
Tiba-tiba aku merasakan ada yang menggerak mendekat kepadaku. Refleks, aku panik. Karena kita masih di kedai kopi. Pukul 10 pagi dan banyak tamu berdatangan. Kamu meraih daguku kemudian mendaratkan bibirmu ke bibir...
Sebuah bunyi pesan singkat masuk. Membangunkan tidurku.
"Hai, maaf. Untuk akhir pekan ini aku betul-betul sibuk harus bekerja. Mungkin lain kali."
Aku menghela nafasku. Membaca dua kali jawabanmu sampai menyadari rasanya tidak akan ada lagi kata 'lain kali'.
Aku balikkan layar handphoneku mengarah ke meja dan kembali ke pekerjaanku yang meletihkan itu.
Gusar di dadaku.
"Monyet."

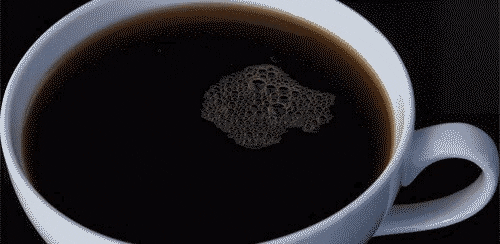
Comments
Post a Comment